
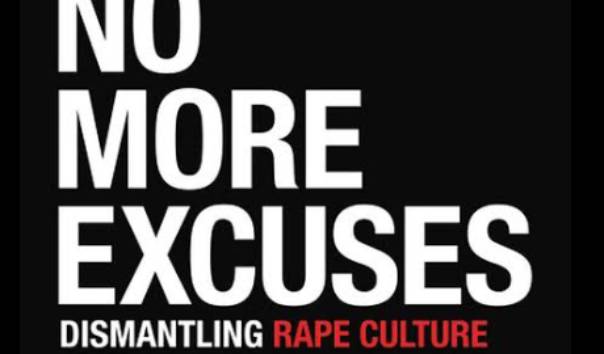
Aktivis hak-hak perempuan, Evelyn Reed dalam bukunya Mitos Inferioritas Perempuan menyebutkan bahwa, ketidakadilan seksual telah terjadi semenjak beribu-ribu tahun yang lalu. Hal ini ditandai dengan corak masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas sosial. Kontruksi ini bermuara pada supremasi laki-laki atas kepemilikan pribadi yang didorong oleh gereja dan negara sebagai institusi formal.
Pembacaan sejarah dalam sudut pandang antropologi ini telah memberi analisis yang tajam atas mitos inferioritas perempuan yang dianggap secara alami terjadi. Pun, pendekatan ini telah membentuk suatu sekat yang kontradiktif dengan dogma teologi.
Artinya, dalam perkembangan sejarah ilmu pengetahuan, perlawanan terhadap obskurantisme (informasi yang dikaburkan) telah mengancam kekuasaan pengetahuan terhadap mistisisme agama sebagai suatu lingkaran yang melanggengkan dominasi patriarki.
Kilas balik sejarah dalam masyarakat komunal primitif telah secara gamblang memperlihatkan bahwa dalam sistem ini, sama sekali menegasi terbentuknya kelas-kelas sosial, yang bermuara pada penindasan seksual.
Saat munculnya kepemilikan pribadi dan penguasan properti oleh dominasi patriarki, semenjak itulah posisi perempuan diterjemahkan secara inferior, dijinakan hingga diartikan dalam fungsi hewaniah. Maka secara jelas konstruksi ini terawat dengan penekanan perempuan sebagai makhluk untuk beranak-pinak. Konstruksi ini dibangun masyarakat kelas untuk melanggengkan ketertundukan perempuan dalam penderitaan biologis.
Selain itu, fungsi perempuan ditundukan dalam pengertian naluri keibuan yang berkorelasi erat dengan mistisisme. Penempatan perempuan sebagai objek dari yang terberkati dan dikuduskan, menjadi sandaran baku bahwa kesucian adalah nilai yang perlu dijaga, tetapi disisi lain, mengalienasi kesadaran dari ketertindasan.
Ketika makna beranak-pinak yang diterjemahkan sebagai fungsi alamiah dari reproduksi perempuan, maka akan terlihat secara jelas bahwa kepentingan besar patriarki yang didominasi kepemilikan pribadi, mazhab kapitalistik (baca;kapitalisme), adalah perpaduan integral kebutuhan akan persalinan yang menghasilkan kelas pekerja secara turun temurun.
Relasi kuasa dalam masyarakat patriarki
Ketika klan matriarkal (garis keturunan dari pihak ibu) digulingkan melalui perombakan masyarakat komunal, hingga pada ketentuan hukum yang berdasarkan pada prinsip patria potestas atau semua penguasaan berada di bawah konstruksi laki-laki dengan sendirinya, kita akan melihat bagaimana hierarki laki-laki muncul secara superior dalam konstruksi relasi kuasa.
Ketika institusi patriarkal memunculkan alienasi terhadap klan matriarkal, disinilah terjadi perang gender sesungguhnya yang memunculkan chauvinisme laki-laki atas kepemilikan pribadi dan hal ini ditandai dengan masuknya alat pertanian modern.
Kapitalisme sebagai mata rantai kekerasan, telah merawat penindasan dari mulai sektor ekonomi, sosial, budaya hingga politik. Ketika perempuan diobjektifikasi sebagai makhluk yang secara fungsi biologis adalah bereproduksi, disinilah relasi kuasa patriarkal menunjukan kekuatannya. Ketertundukan perempuan secara tegas dianggap sebagai hal yang normatif dan direduksi dalam fungsi-fungsi seksual semata.
Penaklukan ini terbukti bermuara pada perilaku yang secara “patologi sosial” selalu bermula dengan rape culture (pemakluman pemerkosaan), cat calling (godaan verbal di jalan), sexist joke (humor seksis), hingga victim blamming (menyalahkan korban). Ini tercermin dalam beberapa pernyataan:
“Salah perempuan itu, siapa suruh pulang malam, akhirnya dilecehkan”, “Laki-laki memang begitu, makanya perempuan jangan berpakaian terlalu terbuka”, atau “Hai cantik, mau kemana?”, “Gerah ya sayang, kok bajunya terbuka?”, “Relaxa yah, Rela diperkosa?”, “Perempuan kalo diperkosa, menikmati juga kok”.
Diksi-diksi ini sangat melecehkan perempuan dan menormalisasi perkosaan dalam masyarakat. Di Indonesia, persoalan kekerasan seksual kerap dianggap sebuah aib, kesalahan korban, kutukan, nasib dan cara berpakaian yang berujung pada ketiadaan empati masyarakat terhadap korban.
Penaklukan tubuh perempuan adalah corak “politik seksual” paling ampuh yang selalu dilakukan oleh negara, agama, lingkungan akademik, organisasi yang mengaku progresif sekalipun, hingga pada lingkup “personal” yang secara struktur sosial memiliki relasi kuasa atas korban.
Masyarakat patriarkal gagal melihat dampak besar perkosaan bagi perempuan, sistem masyarakat merasa berkuasa atas tubuh perempuan, hingga kerap tatanan ini dibungkus secara normatif, dikemas melalui pengontrolan pada tubuh perempuan, dikontrol secara gerakan, regulasi hukum, standar sosial, hingga institusi terkecil yaitu keluarga.
Fenomena Rape Culture hingga penaklukan atas tubuh perempuan
Fenomena rape culture bak jamur di musim hujan, ia tumbuh subur dalam komposisi masyarakat patriarkal yang menganggap pemerkosaan sebagai sesuatu hal yang lumrah terjadi. Pemakluman terhadap perkosaan ini nyatanya telah turut berkontribusi pada pelanggengan dominasi dan superioritas patriarki dalam masyarakat.
Relasi kuasa yang dilestarikan sebagai konstruksi untuk menaklukan perempuan, menjadi sisi paling diskriminatif bagi perempuan dalam mengakses lingkungan yang aman.
Intimidasi, kekerasan, pelecehan, perkosaan, sampai pembunuhan adalah bentukan sistematisasi relasi kuasa yang secara predisposisi dihasilkan dari corak rape culture yang menganggap perkosaan itu lumrah. Kondisi ini cenderung mengabaikan psikis dan situasi korban kekerasan hingga menekan korban untuk bersuara.
Rape culture adalah anggapan yang sangat diskriminatif dalam masyarakat, anggapan ini merawat cercaan bagi korban kekerasan dan menjadi aksioma laten yang terjaga tatanannya sampai pada praktik kekerasan seksual. Saya menyebutnya sebagai “patologi sosial” yang termanifestasi dalam nilai-nilai patriarkis.
Narasi dogmatis ini telah secara kongkrit merantai dan menjadi "sabit unggul" penaklukan atas tubuh dan pikiran perempuan. Ia menjangkit secara sosial, mempengaruhi perilaku dan terpolarirasi secara masif sebagai tatanan.
Membaca Rape culture dalam corak masyarakat yang menerapkan kepemilikan pribadi, tidak hanya dikonstruksikan sebagai properti semata. Dalam pendekatan relasi, ia secara kongkrit termanifestasi dalam hubungan pernikahan ataupun hubungan pacaran. Masyarakat patriarkal merawat ini, dengan metode “klaim” hak milik atas tubuh pasangannya.
Salah satu contoh dari fakta ini terlihat dalam anggapan bahwa konstruksi relasi yang dilegitimasi oleh cinta pada pasangan harus dibuktikan secara kongkrit dengan melayani kepentingan lelaki secara seksual. Kontradiksinya selalu pada tataran pemaksaan hubungan seksual, yang berujung pada kekerasan.
Dalam relasi pernikahan, disebut dengan marital rape (pemaksaan hubungan seks), ini merupakan manifestasi dari segala sesuatu yang telah diproduksi secara historis, dilanggengkan dalam praktek perilaku sosial yang bermuara pada tatanan timpang yang diskriminatif. Sebuah potret konspirasi antara kapitalisme dan patriarki yang merawat perbudakan terhadap perempuan secara masif.***
#lawan